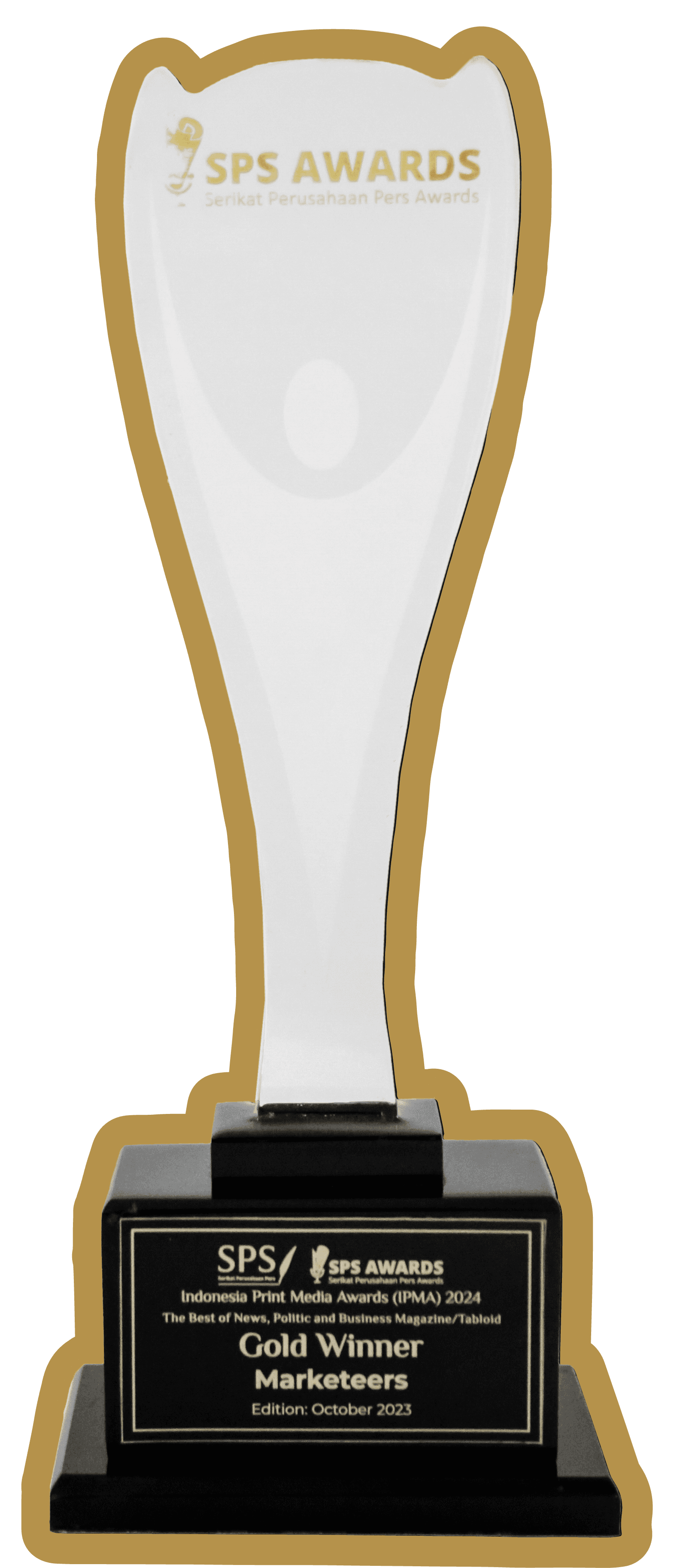Perekonomian dunia, khususnya Amerika Serikat (AS) tengah memasuki era anomali. Meski banyak pihak yang meragukan kepemimpinan Donald Trump, indeks saham acuan Dow Jones Industrial (DJIA) terus mencetak rekor dari waktu ke waktu.
Bahkan, lembaga rating internasional Standard & Poor’s (S&P) mengatakan, DJIA telah naik sebanyak 3,8% di bulan pertama sejak Trump menjabat. Selama ini, hanya ada dua presiden AS yang mampu melebihi prestasi itu. Yaitu Lyndon B. Johnson, Presiden AS ke-36, di mana DJIA naik 6% dalam waktu sebulan setelah dia menjabat dan John F. Kennedy, Presiden AS ke-35, di mana kala itu DJIA naik sebanyak 4,3%.
“Padahal kondisi politik di AS memanas dan Trump mempunyai kebijakan proteksionisme. Tapi bursa saham justru mencetak rekor dari waktu ke waktu,” kata A. Tony Prasetiantono, Kepala Ekonom PT Bank Pertama Tbk di acara PermataBank Wealth Wisdom di The Ritz Carlton, Pacific Place Jakarta.
Kebijakan proteksionisme itu pula yang membuat banyak dana asing keluar dari bursa saham dunia dan kembali ke AS. Hal inilah yang kerap dikenal dengan istilah capital outflow. Hal itu yang terjadi di China yang berakibat pada merosotnya cadangan devisa mereka, dari US$ 4 triliun menjadi US$ 3 triliun pada periode sekarang ini. “Selain balik ke Amerika, banyak investor yang mengalihkan dananya ke Vietnam,” katanya.
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Meski kondisi ekonomi dunia tak menentu, Tony mengatakan fundamental perekonomian Indonesia masih baik. Selain rasio debt to GDP yang masih rendah –jika dibandingkan negara lain-, Indonesia juga baru saja mendapatkan rating investment grade dari S&P.
Kondisi itu menjadikan Indonesia akan kebanjiran capital inflow atau dana asing, salah satunya dari Jepang. “Menurut perhitungan, bakal ada dana dari investor Jepang yang akan berinvestasi di Indonesia. Nilainya mencapai US$ 3-5 miliar. Dan, itu belum terjadi,” kata Arief Managing Partner Ashmore.
Meski fundamental Indonesia baik, bukan berarti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktornya adalah karakter konsumen Indonesia yang mengerem nafsu untuk belanja. “Kredit perbankan hanya tumbuh satu digit. Artinya orang semakin malas berutang. Di satu sisi, Dana Pihak Ketiga (DPK) terus tumbuh. Jadi, ini anomali karena fundamental ekonomi Indonesia masih baik,” kata Tony.