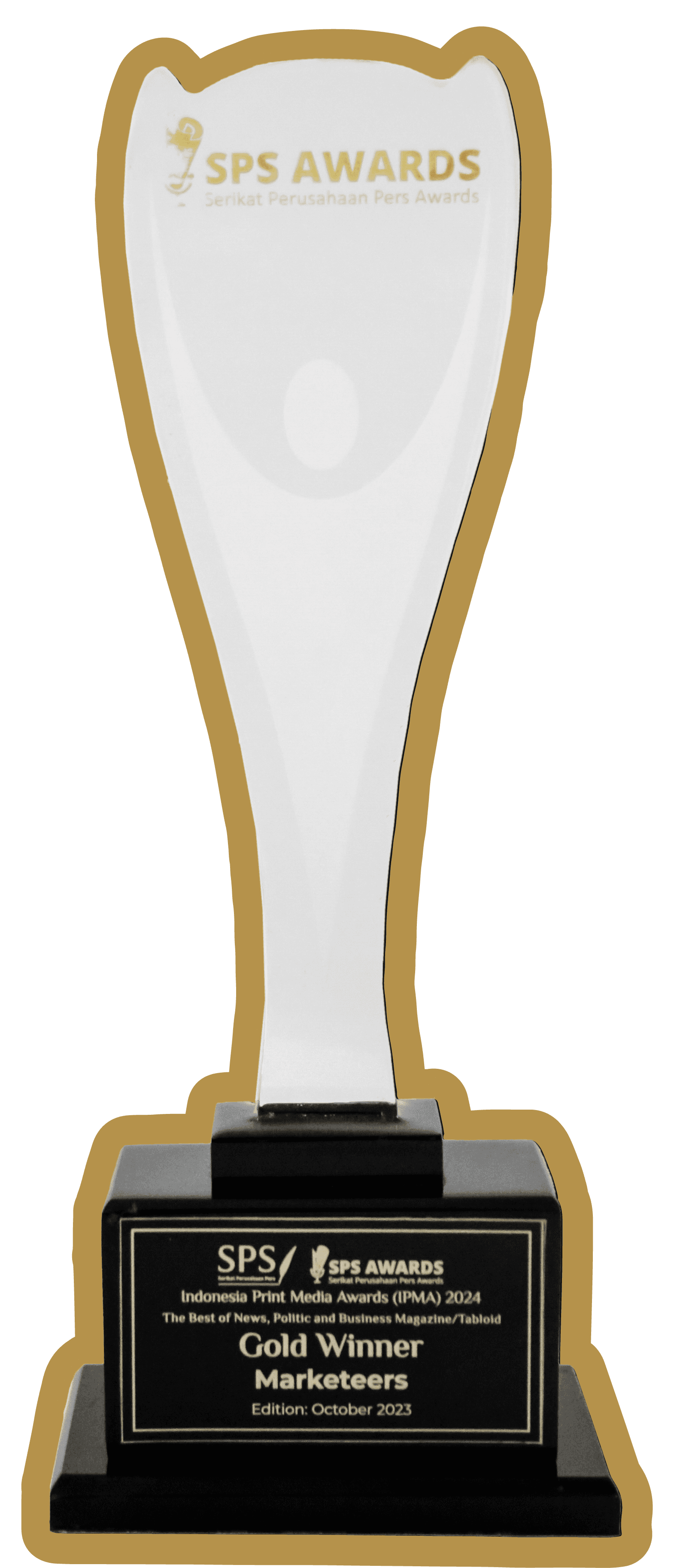Belajar dari Kasus ACT, Pemasar Perlu Ingat Bahwa Brand is Character
Membangun sebuah merek bukanlah pekerjaan singkat seperti dalam cerita rakyat Rara Jonggrang yang meminta Bandung Bandawasa membangun seribu candi dalam semalam. Membangun merek itu pekerjaan bertahun-tahun dan bahkan pekerjaan seumur hidup.
Selain itu, pemasar perlu menyadari bahwa merek itu bisa kuat sekaligus ringkih. Kuat karena merek bukanlah sekadar nama, tetapi juga identitas di mana di dalamnya ada kepercayaan, reputasi, relasi intim dengan pelanggan. Ringkih karena kepercayaan, reputasi, dan relasi tersebut bisa gampang robek atau rusak gara-gara kasus tak baik yang menimpa merek itu. Di era internet yang semakin masif ini, merek yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hancur berantakan dengan gampang hanya dalam sekejap.
Salah satu contoh kasus terbaru belakangan ini adalah kasus yang menimpa Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Mengutip dari Tempo, pada periode tahun 2018 hingga tahun 2020, lembaga ini mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 500 miliar. Angka ini lebih tinggi dibanding lembaga serupa lain, seperti Dompet Dhuafa (Rp 375 miliar) dan Rumah Zakat (Rp 224 miliar).
Tulisan ini tidak akan masuk dalam kasus yang menimpa ACT yang diduga telah melakukan penyelewengan dana tersebut. Tulisan ini hanya menyoroti bagaimana merek ACT sebagai lembaga filantropi yang sudah lama dibangun tercoreng karena kasus tersebut. Angka 500 miliar itu bukan sebatas angka, melainkan indikasi betapa besar kepercayaan masyarakat pada ACT. Sayangnya kepercayaan tersebut terciderai oleh kasus yang sedang viral saat ini.
Brand is Character
Pada masanya, merek atau brand dianggap lebih suci dan keren ketimbang marketing. Merek memuat sesuatu yang magis dan agung meski abstrak. Namun, pada masa di mana konektivitas semakin menguat karena internet, branding mulai dianggap negatif. Banyak orang bilang bahwa branding merupakan aktivitas mempercantik diri alias sekadar kosmetik. Kasarannya, branding merupakan upaya menutup-nutupi apa yang sebenarnya dari sebuah merek maupun perusahaan.
Anggapan dan persepsi semacam itu tentu tidak salah karena tak disangkal bahwa ada banyak merek melakukan branding sekadar untuk pencitraan. Dari persepsi tersebut, pemasar perlu menyadari bahwa brand bukan sekadar nama dan branding bukan pencitraan.
Redefinisi dari merek di era transparan seperti saat ini adalah brand dipahami sebagai character. Sebagai karakter, merek itu memposisikan diri seperti halnya manusia. Karakter tersebut mengacu pada the true self dan bukan sekadar cover atau sampul permukaan saja. Karakter inilah yang menjadi pondasi dari relasi antara merek dengan pelanggannya. Karakter mengacu pada nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang, termasuk juga reputasi, tanggung jawab, kepercayaan, dan sebagainya. Penyelewengan dana jelas menciderai reputasi, kepercayaan, dan tanggung jawab. Ketika karakter buruk muncul, merek itu diambang kehancuran.
Mengapa di ambang kehancuran? Karena kepercayaan masyarakat yang melekat dalam merek itu sirna. Nasihat orang tua Jawa mengatakan, kehilangan harta bukanlah apa-apa, kehilangan nyawa adalah kehilangan setengahnya, namun kehilangan kepercayaan adalah kehilangan segala-galanya.
Dalam konsep Marketing 3.0, karakter merek tersebut sangat ditekankan. Di era human-centric marketing ini, masyarakat juga mulai kuat dalam hal nilai-nilai, seperti solidaritas, kemanusiaan, empati, dan sebagainya. Sayangnya, hal itu juga dirusak oleh perilaku merek yang selama ini dipercaya sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengekspresikan nilai-nilai tadi. Marketing 3.0 sampai hari ini masih menjadi pondasi bagi praktik pemasaran di era digital dan bahkan era yang semakin dan imersif dengan metaverse-nya.
Brand Recovery
Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Demikian juga dengan perilaku pengelola merek yang merusak mereknya dengan perilaku buruk. Tentunya tak gampang melakukan brand recovery. Butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Namun, tentu tetap ada harapan bahwa brand recovery bisa terwujud.
Lagi-lagi pemasar perlu kembali pada pemahaman merek sebagai karakter seperti halnya manusia. Seperti manusia, merek bisa salah dan jatuh, lalu mengakui kesalahan, meminta maaf, memperbaiki diri, dan perlahan bangkit kembali. Bukan sebaliknya, dengan pongah berupaya keras menutupi kesalahan satu dengan kesalahan lainnya. Bila ada merek yang sombong, angkuh, dan berbohong kepada pelanggannya sebenarnya merek tersebut sedang menggali kuburnya sendiri.
Sekali lagi, merek adalah karakter dan branding without character is nothing. Nilai ini masih berlaku hingga hari ini. Dan, sekali lagi, membangun merek bukanlah pekerjaan semalam. Semoga ACT mampu mengembalikan lagi nama baik mereknya.