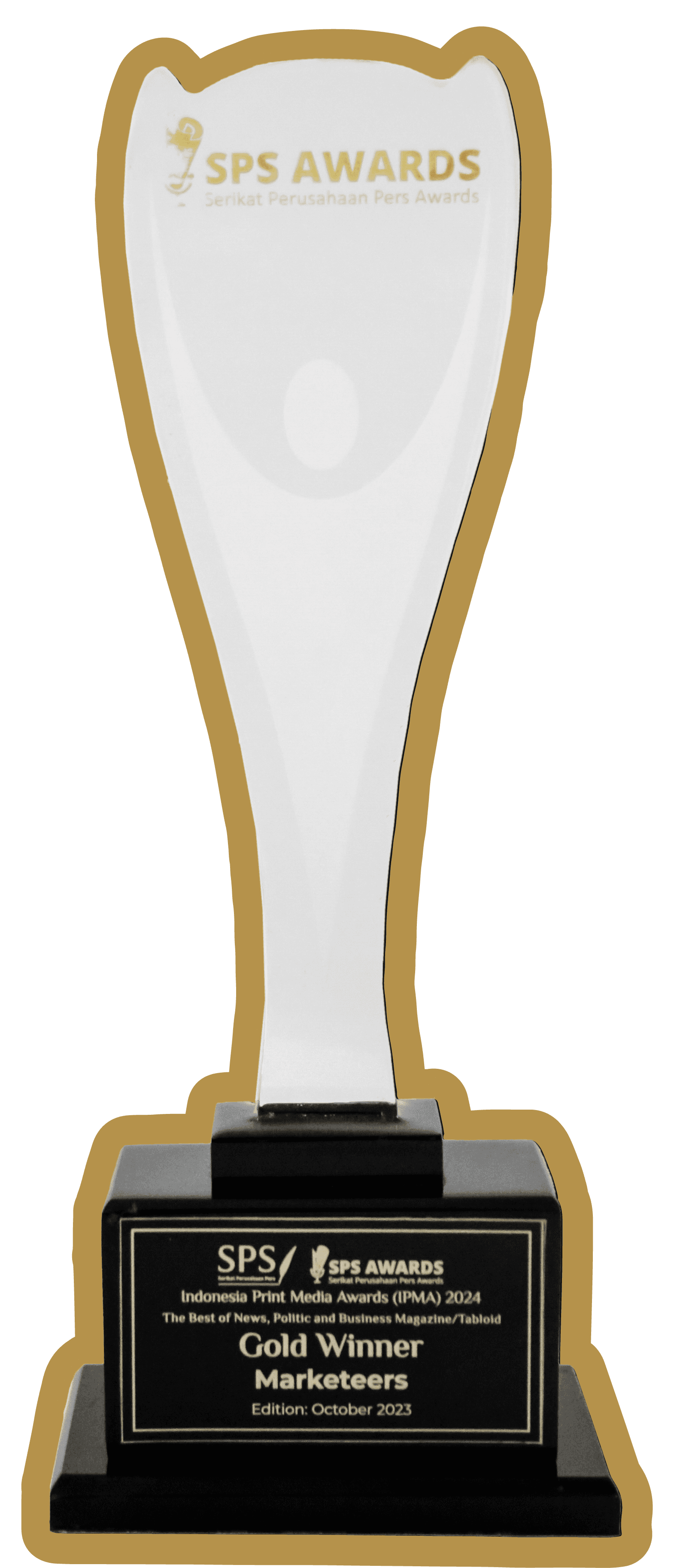Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah awal yang baik untuk memastikan perlindungan data pribadi di Indonesia. Bagaimanapun juga, implementasi UU ini perlu dibarengi oleh literasi digital.
“Selain memperkuat dari sisi regulasi, Indonesia juga masih perlu memperkuat literasi digital dan hal tersebut dapat dimulai sejak usia dini, belajar dari yang kita alami karena pandemic Covid-19,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza dalam siaran persnya, Selasa (4/10/2022).
Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 61 dari 100 negara terkait dengan kesiapan menggunakan internet. Posisi Indonesia lebih rendah dan tertinggal cukup jauh dari negara tetangga seperti Singapura (peringkat 22) dan Malaysia (peringkat 33).
Nadia menambahkan tidak hanya mencakup kemampuan mengoperasikan gawai, laptop dan internet, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang didapat melalui berbagai sumber digital secara bertanggung jawab. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia, sayangnya, tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni.
Faktanya, masyarakat Indonesia cukup rawan terpapar hoaks dan misinformasi, terlibat dalam perundungan siber, serta menjadi target penipuan di dunia maya. Dalam konteks pandemi Covid-19, maraknya misinformasi atau hoaks menunjukkan rendahnya literasi digital dapat memengaruhi usaha pemerintah dan masyarakat untuk menangani pandemi.
Kemampuan literasi digital sangat dipengaruhi dengan kemampuan literasi baca tulis yakni kemampuan membaca, menulis, mencari, menganalisis, mengolah dan membagikan teks tertulis. Sayangnya, performa Indonesia di bidang literasi baca tulis termasuk rendah.
Berdasarkan hasil dari survei Programme for International Students Assessment (PISA) tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 71 dari 79 negara. Dipaparkan hanya 30% peserta didik yang menunjukkan setidaknya kemampuan level 2 dibandingkan dengan 77% peserta didik di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi masyarakat Indonesia adalah kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini. Padahal, literasi digital perlu diasah sejak dari pendidikan dasar.
Tantangan struktural, yaitu ketimpangan akses internet antar daerah juga mempersulit adopsi teknologi. Nadia merekomendasikan beberapa hal untuk memperbaiki literasi digital.
Pertama, mengingat urgensi peningkatan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) harus berpikir ulang dalam menyusun kurikulum mata pelajaran TIK agar sesuai dengan tuntutan zaman. Ada baiknya apabila konten pembelajaran TIK lebih memprioritaskan pengajaran dalam penggunaan dan menyampaikan informasi yang didapat secara daring dengan bertanggung jawab, mengidentifikasi informasi daring yang dapat dipercaya dan cara mengamankan peserta didik selama aktivitas daring mereka.
Kompetensi seperti ini akan sangat relevan dengan tuntutan era digital saat ini. Selanjutnya, materi literasi digital juga harus disertakan dalam pelatihan guru.
Tanpa meningkatkan kompetensi TIK yang rendah dan pedagogi berpikir kritis di antara para guru, mereka tidak akan dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital siswa. Keempat, kemitraan pemerintah dengan para ahli dari sektor swasta juga perlu diperkuat.
Para tenaga ahli eksternal ini dapat membantu pemerintah merumuskan indikator yang relevan untuk kurikulum literasi digital. Terakhir, peningkatan akses dan teknologi Internet, terutama di daerah pedesaan di Indonesia, harus tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital.
Salah satunya lewat kemitraan dengan sektor swasta untuk melengkapi sekolah, terutama di pedesaan, dengan laptop/komputer.
Editor: Ranto Rajagukguk