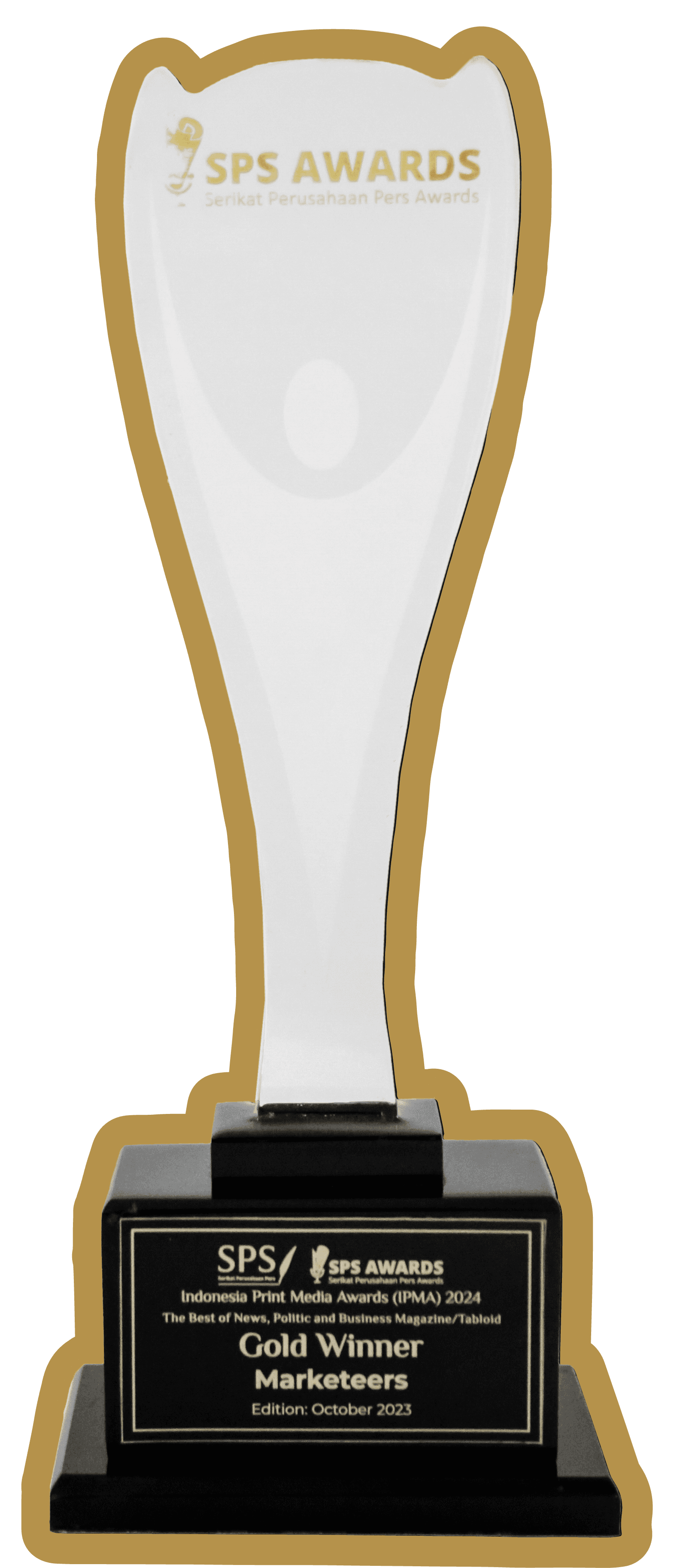Salah satu masalah paling umum yang dihadapi oleh para pemain e-commerce adalah tingginya angka drop cart dan abandoned cart. Ini adalah jumlah keranjang belanja di dalam aplikasi yang sudah terisi oleh beberapa produk, namun ditinggalkan begitu saja tanpa dilanjutkan ke proses pembayaran.
Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak melanjutkan ke proses pembayaran dan meninggalkan begitu saja?
Dugaan awalnya adalah karena sesi belanja online-nya terganggu oleh aktivitas lain yang mendadak harus dilakukan. Contohnya saja panggilan telepon yang masuk ketika sedang dalam proses belanja online, atau ada tamu yang datang atau pekerjaan lain dadakan yang muncul di tengah-tengah sesi tersebut.
Dugaan lain yang muncul adalah karena konsumen yang bersangkutan menemukan produk yang sama atau produk sejenis di aplikasi lain yang lebih menarik sehingga mereka memilih untuk melanjutkan transaksi di aplikasi lain. Walaupun keduanya sering terjadi, namun ternyata ada satu praktik yang makin menjamur, terutama di tengah penetrasi digital commerce yang kian luas, yaitu sesuatu yang dikenal dengan webrooming.
Webrooming adalah fenomena saat konsumen mengawali proses belanja di platform online, namun pada akhirnya membeli secara offline di toko fisik. Praktik ini sering kali terjadi karena beberapa hal.
Pasalnya, produk yang diminati membutuhkan asesmen secara fisik. Produk-produk seperti pakaian yang mana model bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi pembelian, melainkan juga kualitas bahan, ukuran dan bagaimana produk bisa cocok di tubuh konsumen.
Hal ini mendorong konsumen untuk menunda pembeliannya di platform online dan beralih ke toko offline. Mereka bisa touch and feel, mencobanya untuk memastikan kualitas dan kecocokan produk dengan dirinya terpenuhi.
Hal ini juga terjadi untuk produk-produk yang kualitasnya tidak konsisten. Misalnya produk hasil bumi, seperti sayur dan buah.
Hal ini pula yang bisa menjawab pertanyaan mengapa platform belanja produk hasil bumi yang memiliki potensi amat sangat besar karena produk yang dijual punya pangsa pasar yang luas, namun belum berhasil menjadi pemain utama dari bisnis digital lain. Padahal, jika dibandingkan online travel agent, pangsa pasarnya tidak sebesar produk hasil bumi.
Semua manusia yang hidup mengonsumsi hasil bumi, seperti sayur dan buah dalam frekuensi yang amat sangat tinggi, beberapa kali dalam sepekan setidaknya. Artinya, pangsa pasar yang disasar oleh aplikasi e-grocery amat sangat besar.
Sementara itu, tidak semua orang ber-traveling dengan pesawat atau menginap di hotel, apalagi dengan frekuensi yang begitu seringnya. Namun kenyataannya skala bisnis e-grocery business masih belum mengalahkan skala bisnis online travel agent.
Ini terjadi karena ketidak konsistenan kualitas dari sayuran dan buah-buahan karena bukan buatan pabrik. Hal itulah yang membuat tidak sedikit orang melakukan webrooming pada kategori bisnis tersebut.
Praktik webrooming juga bisa terjadi pada produk-produk baru yang mana built quality amat sangat penting sehingga kita butuh memastikan kesesuaiannya berdasarkan gambaran di benak kita dengan mengunjungi toko offline yang menjualnya. Paling tidak kita memastikan kualitasnya dengan melakukan touch and feel.
Praktik webrooming akan makin kuat pada produk-produk fisik yang tergolong high involvement product. Ini terjadi karena esensi dari dorongan konsumen melakukan webrooming adalah karena adanya consumer perceived risk yang besar.
Ini adalah persepsi tentang adanya risiko dari pembelian produk yang muncul karena kurangnya sensory experience terhadap produk tersebut. Pikiran kita was-was untuk mengambil keputusan pembelian tanpa melakukan touch and feel bisa karena memang produk baru, atau mungkin nature product-nya yang tidak konsisten sehingga harus ada asesmen fisik.
Dalam hal ini interaksi fisik pun menjadi mandatory. Secara segment, webrooming banyak dilakukan oleh generasi yang lebih dewasa yang sudah bertransaksi sebelum digital commerce masuk.
Kaum yang sering disebut sebagai digital immigrant ini masih belum percaya penuh terhadap apa yang ditawarkan oleh platform online. Ini terjadi karena mereka terbiasa dan dididik oleh cara belanja offline saat adanya interaksi fisik. Ini pula yang membuat consumer perceived risk-nya relatif lebih tinggi ketika harus berbelanja online.
Sebaliknya, tidak jarang pula kita menyaksikan orang-orang yang berada di supermarket atau toko fisik apa pun yang kemudian sibuk membuka smartphone-nya dan tampak me-review dan membandingkan produk yang ada di hadapannya dengan sesuatu yang ia akses melalui smartphone. Ini adalah praktik yang sering disebut sebagai showrooming, yaitu praktik untuk memulai proses belanja secara offline di toko fisik, namun kemudian berakhir secara online.
Setidaknya ada tiga alasan mengapa ini terjadi. Pertama karena mereka berusaha membandingkan harga yang mereka dapati secara offline di toko fisik dengan pilihan yang tersedia di toko online. Yang kedua adalah berusaha mencari spesifikasi detail tentang produk tersebut.
Ketiga, adalah berusaha mencari social confirmation dari orang-orang yang pernah membeli produk tersebut melalui review yang mudah ditemukan di internet. Mengenai motif untuk membandingkan harga, seperti sering saya sampaikan bahwa manusia, apa pun rasnya memiliki program dasar untuk seek pleasure dan avoid pain.
Harga yang lebih murah untuk produk yang sama diartikan oleh otak kita sebagai pleasure. Sementara itu, harga yang lebih mahal diartikan sebagai pain.
Maka dari itu seberapa pun kuatnya sebuah brand, konsumen tidak bisa meninggalkan tendensi naturalnya untuk tergoda pada harga yang lebih murah, dan ini sering terjadi pada toko ritel. Contohnya saja kita ketahui toko ritel supermarket hanyalah sales channel.
Produk dan merek yang dijual di toko tersebut bisa jadi sama dengan toko ritel sebelah. Maka dari itu opsi untuk membelinya dengan lebih murah menjadi opsi yang cukup menggoda, terlebih ketika experience yang ditawarkan untuk menemukan pembandingnya dan membeli darinya begitu seamless dan frictionless.
Kini, segala macam hal bisa dengan mudah kita temukan dengan bantuan smartphone. Selain harga, berbagai informasi tentang produk tersebut juga semudah membuka smartphone dan melakukan pencarian di mesin pencari.
Karena kemudahan itu pulalah konsumen bisa menurunkan consumer perceived risk-nya dengan melakukan social validation melalui berbagai macam review tentang produk yang bersangkutan yang dengan amat sangat mudah bisa ditemui melalui smartphone.
Konektivitas dan integrasi informasi dan berbagai macam akses ke channel penjualan yang terbangun antara online dan offline cukup memaksa brand owner untuk bisa memanfaatkannya demi kepentingan produk ketimbang menghindarinya. Consumer perceived risk sudah ada sejak dulu kala dan akan terus ada sampai kapan pun.
Teknologi yang membuka akses terhadap berbagai macam channel penjualan lain, informasi produk dan juga kumpulan review dari para pengguna justru membuat consumer perceived risk meningkat. Ketersediaan berbagai macam informasi yang dengan amat mudah diakses mendorong konsumen malah makin memaksakan diri untuk memanfaatkannya.
Toh cuma one click away untuk bisa compare harga, lihat informasi produk dan juga lihat review produk dari konsumen lain. Begitu pikir mereka.
Pilihan untuk tidak menggunakan berbagai macam keistimewaan dari interkonektivitas dan frictionless akses ini memberikan tekanan dan penyesalan yang luar biasa bagi mereka. Maka dari itu mereka menggunakannya.
Brand owner tidak punya pilihan untuk mengoptimalkan omnichannel lebih dari sekadar memesan online dan mengambil di toko fisik, atau membayar di toko fisik dan mendapat barangnya melalui pengiriman seperti platform online. Omnichannel bukan lagi soal sales channel saja, tapi juga soal integrasi informasi yang mana konsumen bisa mendapatkan informasi harga, product knowledge maupun customer review dengan mudah secara online.
Di sisi lain, konsumen bisa melakukan interaksi fisik untuk memastikan product experience sesuai dengan ekspektasi dengan kehadiran toko offline. Kita menyaksikan bagaimana dalam beberapa tahun terakhir produsen mobil sudah memangkas belanja marketing untuk cetak brosur.
Di berbagai pameran, mobil-mobil yang ditawarkan selalu ditempeli sticker dengan QR code yang bisa di-scan untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai produk, harga dan customer review jika diperlukan. Brand owner juga kini dipaksa untuk mengorkestrasi kanal-kanal penjualannya, terutama dalam standardisasi harga jika tidak ingin kehilangan satu atau banyak kanal tersebut.
Keseragaman harga antarkanal harus diutamakan untuk memastikan bahwa konsumen bisa menemukan harga yang seragam di kanal yang berbeda sehingga mereka tidak perlu shift kanal sekadar karena harga yang lebih murah. Pada akhirnya, consumer perceived risk dan natural tendency manusia untuk memaknai harga yang lebih murah sebagai pleasure harus menjadi dasar untuk membangun strategy push marketing.
Sementara itu, di sisi lain, ketersediaan berbagai macam informasi yang terintegrasi yang bisa didapatkan dengan amat sangat mudah bisa dijadikan sebagai pull marketing untuk membuat integrasi kedua kanal ini menjadi saling melengkapi ketimbang saling membunuh.