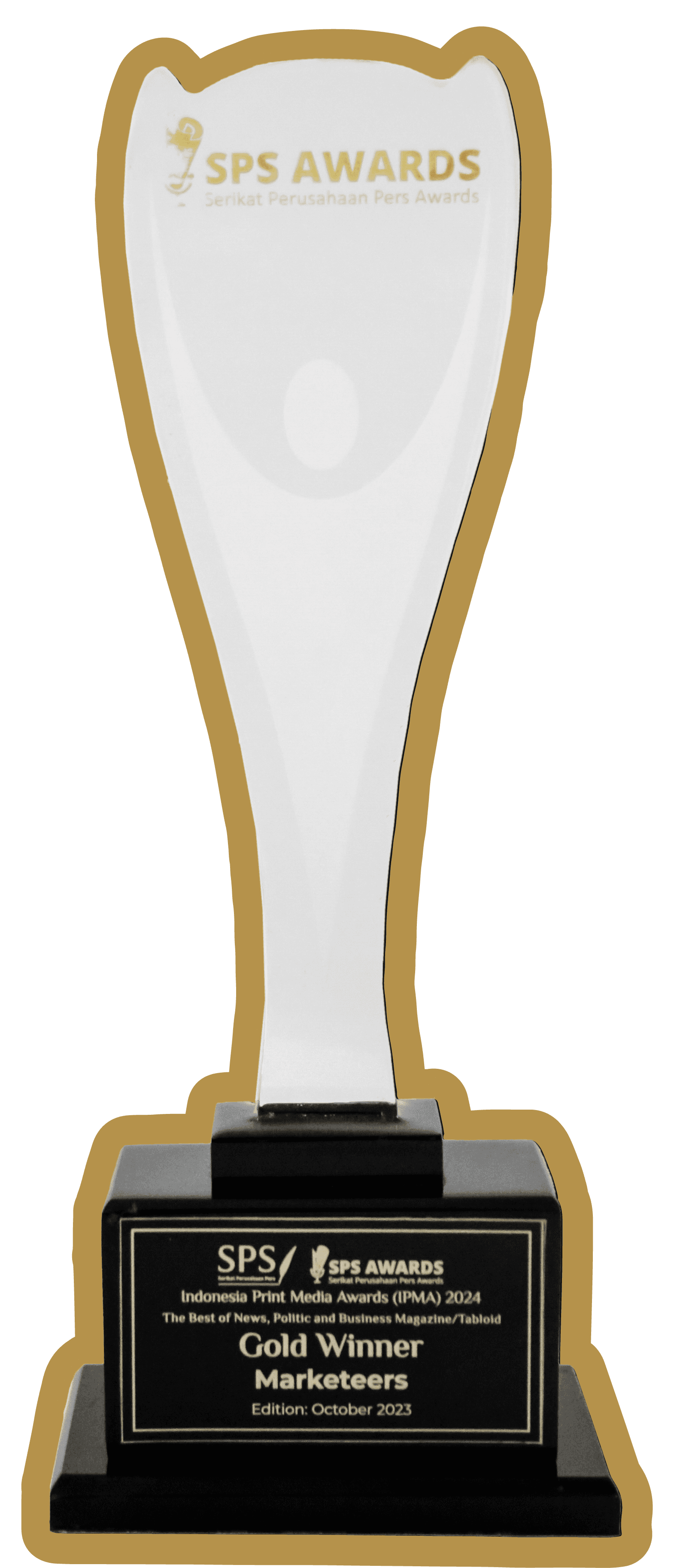Teknologi memang keren namun tak jarang sangat merepotkan dan bikin geregetan. Pekan lalu, misalnya, santer dikabarkan data Bank Indonesia dibobol oleh Wizard Spider, geng peretas asal Rusia. Mereka menggunakan ransomware Conti dan mencuri sebanyak 487,09 MB data milik bank sentral. Geng ini kini telah menjadi target Interpol, FBI, maupun Europol.
Tahun lalu, 91 juta data pengguna dari pemain e-commerce Tokopedia dikabarkan bocor. Data tersebut berupa nama lengkap, nomor telepon, hingga email. Sebelum dibagikan gratis, data tersebut sempat dijual dengan harga US$ 5.000 atau setara dengan Rp 70 juta.
Kasus bank sentral dan Tokopedia itu hanyalah dua dari ribuan atau bahkan jutaan kasus yang terjadi dalam dunia digital. Serangan siber ini bisa menimpa siapa saja, entah itu negara, perusahaan, komunitas, hingga setiap orang. Bahkan, organisasi yang diandaikan memiliki tingkat keamanan superwahid, seperti CIA, FBI, NASA, dan BSSN ternyata tak luput dari serangan peretas ini.
Teknologi memang berwajah ganda. Satu sisi menyuguhkan segudang manfaat dan keistimewaan bagi umat manusia saat ini yang tak ditemukan di masa lalu. Sisi satunya menyodorkan aneka risiko dengan tingkat risiko supertinggi dan tak terbayangkan sebelumnya.
Dua dekade lalu, dua sosiolog Ulrich Beck (Jerman) dan Anthony Giddens (Inggris) kompak menyatakan bahwa modernitas dengan serangkaian teknologi maju selalu menyuguhkan risiko-risiko. Beck menyebut masyarakat di era ini sebagai masyarakat risiko (risk society).
Risiko ini bukan risiko eksternal, seperti bencana alam gempa bumi, gunung meletus, maupun tsunami. Melainkan risiko buatan (manufactured risk) sebagai konsekuensi kemajuan peradaban manusia, seperti nuklir, senjata biologis, kejahatan siber, peretasan, hoaks, carding, dan aneka risiko yang membonceng internet dan teknologi digital lainnya.
Kesenjangan Digital
Kita sepakat bahwa digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Sayangnya, untuk menggapai kehidupan yang sepenuhnya digital, masih ada sejumlah tantangan. Salah satunya, kesenjangan digital atau digital divide. Istilah ini tak sebatas mengacu pada gap antara komunitas masyarakat yang bisa dan belum bisa mengakses teknologi.
Seperti diungkap dalam buku Marketing 5.0: Technology for Humanity (Wiley, 2021), digital divide ini mengacu pada kelompok pembela (advocates) dan kelompok pengkritik (critics) digitalisasi. Rupanya wajah ganda digitalisasi juga membawa polarisasi cara pandang pada digitalisasi tersebut. Satu melihat peluang dan satu lagi melihat ancaman.
Lima Ancaman
Sedikitnya ada lima ancaman dari digitalisasi yang memunculkan ketakutan di hati sebagian warga dunia. Pertama, automasi dan hilangnya pekerjaan manusia. Bisnis yang menggunakan teknologi automasi seperti robot dan artificial intelligence (AI) akan merampas pekerjaan manusia. Padahal tak semua pekerjaan manusia bisa digantikan robot. (Baca juga Marketing 5.0: Machine is Cool, Human is Warm)
Kedua, kepercayaan dan ketakutan pada yang tak diketahui. Dunia digital ibarat belantara mahaluas yang memesona sekaligus menakutkan. Menakutkan karena masih banyak bagian dari belantara itu yang belum manusia pahami. Sebuah pertaruhan ketika manusia menaruh percaya pada mesin untuk urusan keuangan maupun tindakan medis. Manusia juga khawatir kelak AI memiliki kecerdasan melampaui kecerdasan manusia. (Baca juga Teknologi untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Teknologi)
Ketiga, privasi dan keamanan. AI bekerja berdasarkan data. Berbasis data, perusahaan dengan bantuan AI mampu melakukan personalisasi dan kustomisasi pada pelanggan sehingga mereka merasa diistimewakan. Namun, data-data privasi tersebut bisa disalahgunakan untuk kejahatan maupun kepentingan komersial. Dunia digital juga rentan dengan kejahatan. Persis seperti serangan siber yang menimpa Bank Indonesia dan Tokopedia tadi. (Baca juga 13 Paradoks dalam Masyarakat New Wave)
Keempat, filter bubble dan era pascakebenaran. Mesin pencari dan media sosial telah mengambil alih media tradisional sebagai sumber pertama informasi di era digital. Keduanya memiliki pengaruh membentuk persepsi dan opini yang tak jarang jauh dari hal faktual dan kebenaran. Muncullah post-truth yang ditandai dengan susahnya membedakan fakta dan kebohongan.
Kelima, gaya hidup digital dan efek samping perilaku. Kecanduan gawai maupun konsumsi layar berlebihan berpotensi merusak aktivitas keseharian. Meskipun di sisi lain pemanfaatan platform digital membuat hidup manusia lebih efisien.
Lima Peluang
Selain ancaman, digitalisasi mengusung janji-janji dengan aneka peluang baru bagi pengembangan hidup manusia. Ada lima nilai yang diusung digitalisasi. Pertama, ekonomi digital dan penciptaan kemakmuran. Pertama dan terutama digitalisasi memungkinkan bangkitnya ekonomi digital yang mengusung kemakmuran secara masif.
Kedua, big data dan pembelajaran sepanjang hayat. Platform dan ekosistem digital mengubah cara manusia berbisnis. Dengan lebih ramping, mereka menghubungkan perusahaan, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dalam komunikasi dan transaksi tanpa batas.
Ketiga, smart living dan augmented being. Dalam dunia yang terdigitalisasi penuh, kita akan hidup dalam rumah dan lingkungan cerdas dan terhubung. Robot siap menjadi asisten pribadi kita. Teknologi 3D printing siap mewujudkan barang yang kita maui. Kendaraan otonom siap membawa kita pergi. Dunia virtual akan semakin imersif dengan perangkat VR dan AR. Bahkan kelak, semua konektivitas akan terjadi melalui chip yang ditanamkan di dalam tubuh kita.
Keempat, peningkatan kesehatan dan hidup yang lebih lama. Bioteknologi maju memungkinkan manusia hidup lebih lama. Dengan big data, AI bisa memungkinkan penemuan obat baru dan keputusan medis dengan mengusung personalisasi dalam diagnosis dan tindakan medis. Neuroteknologi bakal menjadi jawaban atas gangguan otak.
Kelima, keberlanjutan dan inklusivitas sosial. Digitalisasi memainkan peran penting dalam menjamin kelestarian lingkungan. Ini ditandai dengan hadirnya kendaraan listrik, misalnya. Atau AI yang membantu mengurangi limbah dan membangun ekonomi sirkular.
Necessary Evil
Meski berwajah ganda, sekali lagi digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Di antara penolakan dan penerimaan digitalisasi, muncul apa yang disebut necessary evil. Istilah ini mengacu pada pemahaman bahwa meskipun membawa segudang risiko dan ancaman, digitalisasi tetaplah menjadi pilihan terbaik bagi perusahaan atau organisasi daripada tidak mengadopsi digitalisasi sama sekali.
Andaipun misalnya saat ini perusahaan belum merasakan keuntungan dari digitalisasi dan malah merasa rugi, digitalisasi tetaplah pilihan terbaik. Di antara dua hal yang sama-sama rugi, pilihlah yang ruginya paling sedikit. Dalam konteks ini, sebagai necessary evil, digitalisasi adalah keharusan. Padahal, sejatinya digitalisasi itu lebih banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia ketimbang mudaratnya. (Simak juga podcast ANALISIS Ep. 02 Transformasi Digital)
Mengakhiri polarisasi pandangan tentang digitalisasi ini, kita perlu menyelami lebih dalam unsur manusia dalam teknologi-teknologi maju di mana teknologi sejatinya merupakan sarana manusia mencapai tujuan hidupnya dan mewujud dengan terinspirasi dari kemampuan manusia (human-inspired tech). Lalu memanfaatkan teknologi tersebut untuk kehidupan terbaik bagi umat manusia. Saatnya, kita membangun era technology for humanity.