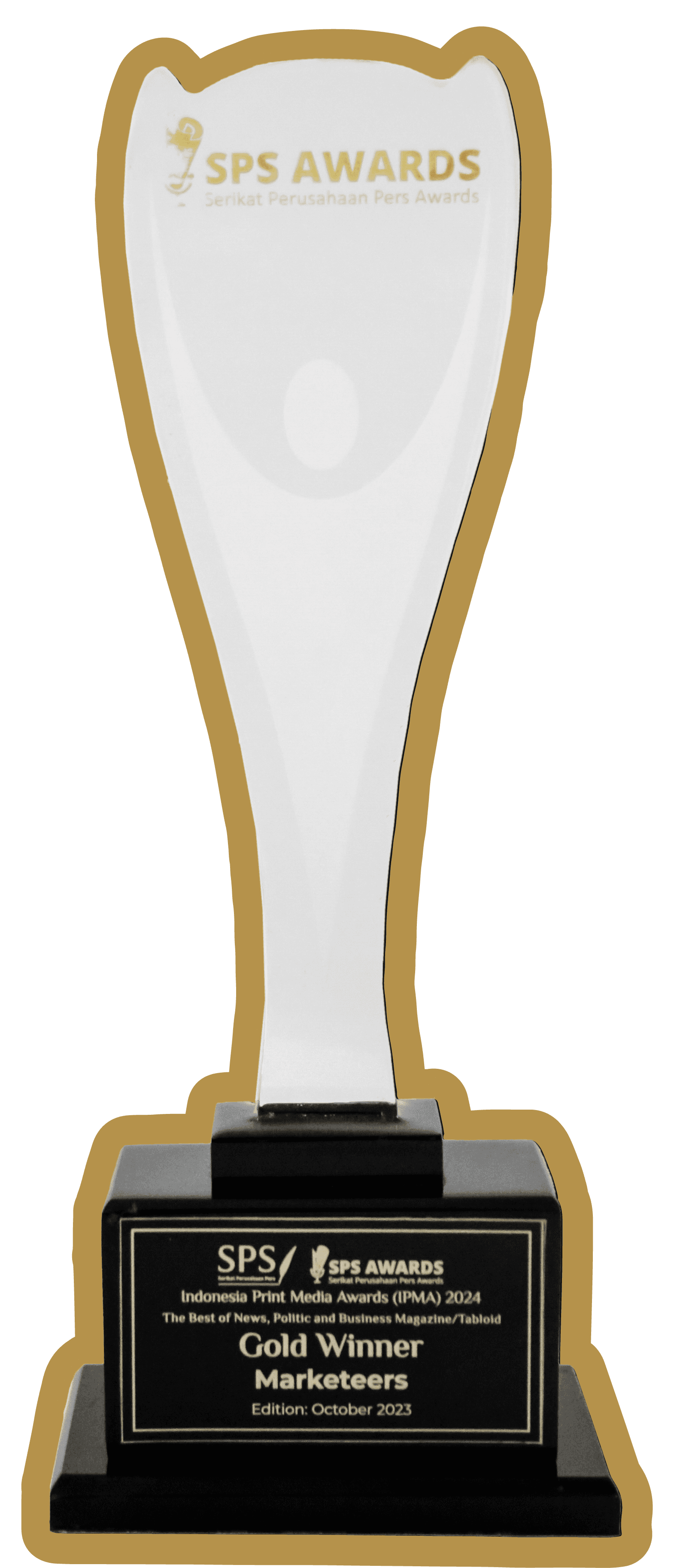Siapa di antara Anda yang sebelum bergabung ke sebuah perusahaan sudah berangan-angan untuk menjalankan ide-ide marketing yang sudah terpikir untuk merek yang akan Anda tangani itu? Banyak pemasar yang sejak dari proses wawancara di sebuah perusahaan sudah mulai membayang-bayangkan apa yang akan dia lakukan ketika bergabung di perusahaan itu.
Studi kasus yang diberikan oleh perusahaan pada saat proses rekrutmen sering kali memantik ide-ide cemerlang. Dan, kita para pemasar memang sering kali tidak bisa ditantang oleh hal-hal semacam ini.
Tantangan datang dan kita pun menyambutnya dengan antusias. Sayangnya, banyak dari kita yang mengalami hal ini pada akhirnya harus kecewa karena ide-ide cemerlang itu tidak mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang juga terlibat.
Tidak jarang, ide-ide itu gugur di tangan orang-orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang marketing. Sebab itu, saya tidak pernah melihat kemampuan seorang pemasar sekadar dari kampanye-kampanye yang berhasil dijalankan.
Untuk bisa membuat kampanye-kampanye brilian itu muncul, butuh lebih dari sekadar pemikiran-pemikiran kreatif, tapi juga kemampuan memengaruhi dan menjual ide ke para stakeholder. Berhasil atau tidaknya kita menjual ide tersebut juga tergantung dari kemampuan kita mengatasi berbagai macam bias psikologi yang sering muncul.
Knowledge Curse Bias
Dalam komunikasi sehari-hari, kita berkomunikasi dengan mengambil wawasan pengetahuan kita. Makin dalam pengetahuan kita terhadap suatu hal, kian kompleks pula kosa kata dan penjelasan kita akan hal tersebut.
Inilah yang menciptakan tantangan lebih untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kurang mengerti bidang itu. Marketing merupakan salah satu spesialisasi yang kompleks.
Banyak kosa kata dan istilah-istilah teknis yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. ROAS, CTR, CPM, Open Rate, high involvement product, low involvement product, upper funnel, bottom funnel dan banyak lagi istilah-istilah yang butuh penjelasan lebih lanjut untuk bisa dicerna orang awam.
Knowledge curse bias merupakan kecenderungan seseorang dengan pengetahuan yang dalam untuk jadi lebih sulit dimengerti oleh orang lain. Sesederhana karena ia tahu banyak hal yang membuatnya lebih menguasai sesuatu namun sulit untuk dimengerti oleh mereka yang tidak menguasainya.
Knowledge curse bias sering kali jadi batu sandungan ketika orang-orang marketing berusaha menjelaskan apa yang mereka kerjakan dan harapan akan dampaknya kepada bisnis. Orang-orang dengan latar belakang berbeda termasuk orang finance, produk, bahkan sales sering kali kesulitan memahami thinking process orang-orang marketing.
Bukan karena marketing plan-nya tidak jelas, tapi lebih karena knowledge curse bias ini.
Resulting
Tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini yang terjadi tanpa konsekuensi. Steroid dan berbagai suplemen pembesar otot yang punya dampak instan, punya konsekuensi kesehatan. Produk-produk instan dalam kemasan punya konsekuensi kesehatan karena mengandung bahan pengawet.
Butuh waktu sembilan bulan buat seorang ibu mengandung hingga melahirkan. Dan ini tidak bisa digantikan dengan mencari sembilan orang ibu yang masing-masing mengandung satu bulan.
Begitu juga dengan marketing. Butuh waktu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang instan tanpa punya konsekuensi.
Sayangnya persaingan bisnis yang makin gencar seiring dengan tuntutan karier sering kali memaksa perusahaan untuk mencari hasil-hasil instan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ketimbang memilih untuk membangun “otot-otot” pertumbuhan organik, perusahaan seringkali sibuk mencari “steroid” untuk pertumbuhan bisnis yang instan.
Diskon dan subsidi bakar uang yang membabi buta, berbagai macam aktivitas media sosial dan content marketing yang sekadar mencari sensasi untuk jadi viral dan dibicarakan banyak orang dan berbagai macam aktivitas lainnya sering kali dilakukan. Kita menilai keberhasilan dari apa yang kita lakukan hanya dari hasilnya.
“Ah, sudahlah, kasih diskon saja yang besar. Nanti, penjualannya naik pesat”, atau “Kita bikin saja sayembara bagi-bagi uang di media sosial, nanti pasti viral.
Kemudian view, engagement dan share-nya jadi tinggi”, begitu mungkin pikir banyak orang. Sayangnya sama seperti bagaimana steroid merampok kesehatan di masa yang akan datang, diskon membabi buta dan aktivitas asal bikin sensasi juga mengikat erat merek kita di titik bawah yang akan sulit bagi kita meningkatkannya di masa datang.
Namun, itu pula area di mana orang-orang marketing lagi-lagi harus berhadap-hadapan dengan mereka yang tidak mengerti marketing. Karena pada akhirnya kitalah yang harus menanggung akibat dari rusaknya merek akibat aktivitas-aktivitas instan yang kita jalankan.
Sebuah strategi sebaiknya tidak dinilai dari hasilnya saja, karena toh orang mabuk yang menyetir juga bisa sampai tujuan tanpa mencelakai orang lain.
Logic Bias
Satu bias lagi yang sering kali jadi penyebab perseteruan antara orang-orang marketing dan orang non-marketing adalah kecenderungan untuk menilai strategi marketing hanya dengan kacamata logika. Manusia adalah makhluk munafik, pada kehidupan sehari-hari kita sering kali mengambil keputusan yang tidak logis.
Namun, kita sering kali memaksakan terpenuhinya logika untuk menilai sesuatu layak dilakukan atau tidak. Mengapa kita mau membayar mahal untuk iPhone dengan spesifikasi dan nilai teknis yang sama dengan merek Android lain yang lebih murah?
Karena ada faktor merek. Dan sayangnya merek bukanlah domain logika. Mengapa kita mau bayar lebih mahal untuk membeli pakaian dalam Victoria Secret yang tidak akan dilihat oleh banyak orang ketika kita menggunakannya?
Karena ketika kita menggunakan pakaian dalam Victoria Secret kita merasa lebih seksi, bahkan walaupun tidak ada yang melihatnya. Dan ini bukanlah sesuatu yang logis.
Banyak ide-ide marketing yang tumbang di meja meeting jauh sebelum sempat dieksekusi hanya karena gagal untuk memenuhi aspek-aspek logis. Seolah-olah keputusan pembelian konsumen 100% logis.
Availability Bias
Salah satu bias yang paling sering terjadi di dalam diskusi-diskusi marketing adalah availability bias. Ini adalah kecenderungan kita untuk menganggap sesuatu yang available untuk kita sebagai sesuatu yang merepresentasikan kelompok yang kita bicarakan.
“Kita pakai KOL ini saja, saudara-saudara saya banyak yang follow dia”, “Kayaknya kemasannya harus kita ganti deh, mama saya saja tidak tertarik melihatnya”, begitu cuplikan komentar-komentar yang sering muncul di ruang meeting. Kita menggunakan informasi yang available untuk kita, termasuk dari keluarga dan orang dekat kita seolah-olah merek kita menyasar keluarga dan orang terdekat kita saja.
Bias ini pula yang juga sering kali mendorong marketer-marketer tak berintegritas untuk memasang iklan di media-media yang sering dilihat atasannya. Pasang billboard di dekat rumah atasan, atau di dekat kantor.
Pasang iklan di portal atau media yang dikonsumsi secara reguler oleh atasan. Tujuannya agar atasan melihat “kerja” sang bawahan, hanya karena kebetulan available di hadapannya.
“Kamu kerjanya apa sih, ngurusin marketing kok enggak keliatan? Saya aja enggak pernah lihat iklan kita”, begitu komentar paling sering kita temui.
Collective Bias
Ini adalah tendensi kita untuk lebih merasa yakin ketika merancang sebuah strategi secara kolektif. Kita sering mendengar istilah “lebih banyak kepala lebih baik” dalam merumuskan strategi pemasaran. Sayangnya, prinsip ini tidak selalu berhasil dengan baik.
Sebaliknya banyak kasus-kasus di mana musyawarah malah menurunkan kualitas output ketimbang meningkatkannya. Contoh paling sering terjadi di dunia marketing ada pada diskusi pembuatan materi kreatif.
Sering kali tim kreatif dan tim marketing yang sudah mempersiapkannya harus mendapat persetujuan dari manajemen. Dalam praktiknya, manajemen sering kali memberi persetujuan dengan satu syarat, yaitu masukan-masukannya diakomodir.
Tidak jarang masukan-masukan ini lebih banyak merusak jalan cerita dari video yang dibuat atau layout design yang disiapkan. Dalam prosesnya, pembuatan materi kreatif sering kali muncul pada sebuah ide setelah melalui thinking process yang panjang.
Dimulai dengan mengerti consumer insight-nya, untuk kemudian datang dengan ide-ide kreatif yang berusaha menyelesaikan tensi yang dihadapi konsumen. Sayangnya, di tahap persetujuan akhir, tidak jarang manajemen yang terlibat mengomentari ide-ide kreatif itu tidak dengan konteks yang sama dengan bagaimana tim kreatif berpikir.
Sehingga sudut pandangnya berbeda, dan hasilnya mirip seperti mencampuradukkan dua buah lagu yang berbeda temponya. Manajemen sering kali memberi persetujuan sesederhana karena kemauannya sudah diakomodir ketimbang melihat kualitas output secara netral dalam konteks yang relevan.
Marketing dalam kodratnya sebagai kombinasi science dan art yang akhirnya membutuhkan sentuhan logis dan juga magis. Sebab, marketing harus selalu berusaha mengerti konsumen yang terkadang rasional tapi juga emosional dan sering kali memunculkan kompleksitas dalam berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Dan, kompleksitas tertinggi dari marketing adalah karena subjek yang membuat marketing strategy, subjek yang menilai dan memberi persetujuan, serta objek yang dituju adalah sama-sama manusia. Setiap manusia pun punya biasnya masing-masing.
Kesamaan ini menjadi kemewahan jika kita bisa menanggalkan perspektif kita yang berbeda dan memilih untuk menggunakan perspektif, konteks dan frekuensi yang sama.