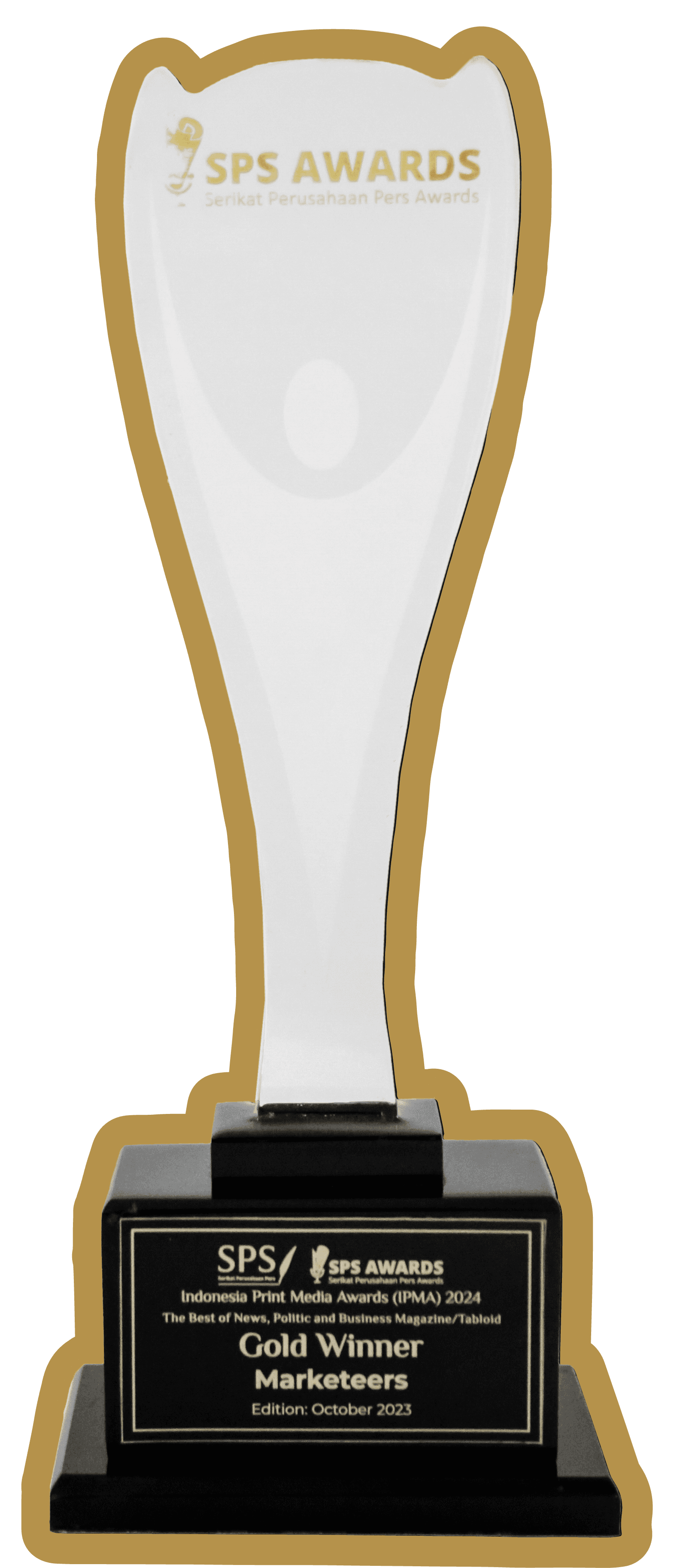Untuk satu postingan di akun Instagram Cristiano Ronaldo, merek perlu merogoh kocek hingga US$ 3,23 juta (sekitar Rp 51 miliar). Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada public figure dunia macam Leo Messi dengan tarif satu postingan Rp 41 miliar dan Selena Gomez Rp 40 miliar.
Ketiga tokoh tersebut memang punya ratusan juta followers di Instagram. Sehingga jika algoritma Instagram yang mendorong hanya 1% dari total follower, maka organic exposure yang dihasilkan masih 5 juta-an, bahkan lebih. Angka yang fantastis.
Influencer marketing tidak hanya membuka kesempatan untuk para selebritas dan tokoh sekelasnya. Namun, juga membuka pintu rezeki bagi mereka yang bukan “selebritas” untuk bisa punya tarif endorsement yang tidak kalah dari selebritas.
Lihatlah Arief Muhammad, Gen Halilintar, Ria Ricis, dan masih banyak lagi orang yang tidak terkenal di televisi layaknya para selebritas namun bisa menghasilkan pundi-pundi yang sama sekali tidak kalah dibandingkan selebritas sekalipun. Influencer social media memiliki daya tawar yang menarik dengan banyaknya orang yang mengikuti mereka.
Brand owner pun mulai melihat mereka sebagai “media” di mana merek bisa memanfaatkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Persis seperti bagaimana merek menggunakan media-media massa untuk bisa mendapatkan tambahan eksposur ke target pasar yang diinginkan.
Namun, jika dihitung secara apple to apple, cost per impression yang mereka tetapkan masih relatif jauh lebih tinggi dibandingkan cost per impression yang ditawarkan sebagian besar media massa. Ini bisa terjadi karena influencer punya nilai lebih dari sekadar menjangkau audiens yang lebih luas, tapi juga memberikan pengaruh lebih besar dibanding media massa yang bersifat dingin dan minim pengaruh.
Pertanyaan besarnya, bagaimana mereka bisa punya pengaruh yang besar pada audiens dan follower mereka?
Rational Level
Pada tahap rasional, influencer media sosial memiliki pengaruh setidaknya dengan dua cara. Pertama adalah pengaruh yang muncul akibat kredibilitasnya.
Setiap influencer memiliki vertical niche-nya masing-masing. Ada yang dikenal karena keahliannya di bidang otomotif seperti Fitra Eri. Ada yang dipercaya reputasinya dalam bidang olah tubuh seperti Ade Rai.
Tidak sedikit pula yang dikenal dan dipercaya akan reputasinya di bidang gadget, mulai dari perangkat komputer, tablet, ponsel, dan berbagai produk-produk teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka membangun reputasinya sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan di bidangnya masing-masing tersebut.
Baik melalui pendidikan formal atau sekadar konsistensi dan jam terbang yang baik untuk menekuni bidang tersebut. Amat sangat masuk akal ketika kita sedang mempertimbangkan membeli sebuah produk untuk bertanya atau mencari tahu pendapat dari orang-orang yang dianggap kredibel di bidangnya.
Kalau mau tahu mobil apa yang OK, ya baiknya tanya Fitra Eri. Kalau mau tahu bagaimana kita bisa membuat sebuah program untuk membangun massa otot maka bertanyalah pada Ade Rai.
Celah kedua bagi sebagian influencer untuk bisa punya pengaruh pada konsumen adalah dengan menjadi “representasi” dari segmen konsumen yang ingin dituju. Mereka tidak bisa dibilang expert bukan karena mereka kurang baik, namun lebih karena subjek yang berusaha dimiliki adalah yang bukan hitam putih atau benar salah. Melainkan subjek yang bisa sangat subjektif segment by segment.
Bidang-bidang, seperti travel, makanan, kecantikan, dan fesyen termasuk beberapa di antaranya. Berbicara mengenai travel, ini bukan masalah benar atau salah, tidak ada hitam putihnya.
Ini juga bukan sekadar bagus atau jelek, karena bagus untuk segmen tertentu bisa berarti jelek untuk segmen lain. Karena itu, kekuatan mereka dibangun di atas pilihan untuk bisa “mewakili” segmen tertentu dengan menjadi sejalan dengan selera segmen itu.
Misalnya, ketimbang berusaha mengangkangi bidang travel saja, mereka pun mengambil persona yang lebih spesifik. Budget traveller misalnya, atau persona traveller yang selalu memilih berbagai macam destinasi, moda transportasi dan akomodasi yang paling mewah.
Sehingga kontennya bisa terasa seperti “flexing” bagi sebagian orang alih-alih sebagai saran dan review sebuah perjalanan. Kelompok ini cukup cerdik mengenal pasarnya, dan secara konsisten membangun personal brand yang sesuai dengan persona segmen yang dituju.
Bagi konsumen, untuk bidang-bidang tertentu yang bisa amat subjektif, referensi yang terasa relevan dengan mereka bukan sekadar benar atau salah, tapi lebih mengenai apakah ini merepresentasikan gaya hidup, ketertarikan, selera dan daya beli saya.
Beyond Rational Level
Alasan-alasan di kelompok kedua tentang bagaimana influencer bisa memiliki pengaruh yang sebegitu kuatnya berkutat melebihi dari pertimbangan-pertimbangan rasional yang logis. “We’re not thinking machine who also think, we are feeling machine who also think”, begitu perkataan Antonio Damasio dalam melihat tendensi manusia dalam menyerap informasi, berpikir, mengambil keputusan dan juga bersikap.
Sebab itu, sering kali alasan-alasan rasional tidak cukup bisa memuaskan berbagai macam pertanyaan kita tentang bagaimana manusia bersikap, termasuk dalam konteks influencer marketing. Jenis pertama dari pengaruh beyond rational terjadi karena idol effect, yaitu kecenderungan untuk menirukan atau mengikuti apa yang dilakukan dan direkomendasikan oleh idola.
Alasan paling mendasar mengapa kita sebagai social media user mem-follow seorang influencer adalah karena kita menyukai mereka dalam tingkatannya masing-masing, orang per orang. Kita mem-follow mereka karena tidak ingin ketinggalan informasi tentang dirinya.
Ketika kita menyukai seseorang kita punya kecenderungan untuk bersikap dan menggunakan banyak hal yang berhubungan dengannya. Sama seperti ketika kita naksir seseorang di bangku sekolah dulu, kita mendadak menyukai lagu yang ia sukai, kita mendadak suka membeli makanan yang ia sukai.
Menyukai seseorang diartikan otak sebagai pleasure. Maka dari itu otak secara bawah sadar akan terus mencari cara agar ingatan tentang orang yang kita sukai muncul kembali di pikiran, karena dengan begitu pleasure center di otak kita akan teraktivasi.
Membeli dan menggunakan apa yang ia sukai adalah salah satu contohnya. Dengan begitu, otak kita bisa memelihara ingatan indah tentangnya dan kita berbahagia sekaligus kecanduan.
Hal yang sama terjadi dengan influencer. Influencer pada tahap tertentu punya idol factor, pengaruh untuk membuat orang mengikuti apa maunya, karena dengan begitu kita sebagai followers-nya bisa memelihara rasa bahagia karena telah berbuat sesuatu untuknya dan kemudian memelihara ingatan indah tentang dia di otak kita.
Ketika sudah di tahap tertentu, idol factor ini pun bisa makin besar dan menciptakan halo effect, yaitu kecenderungan kita untuk mempercayai pilihan dan kemampuan orang yang kita sukai melebihi dari faktanya. “Dia itu kan selebgram dengan banyak follower, jadi enggak mungkin asal-asalan pilih produk lah.” Begitu pembenaran otak kita.
Padahal, membangun followership di Instagram adalah kemampuan yang benar-benar berbeda dengan pengetahuan tentang sebuah produk kecantikan misalnya. Namun, “kecintaan” kita padanya sudah membutakan dan membuat kita percaya pada apa pun yang ia katakan bahkan walaupun itu bukan keahliannya.
Level selanjutnya dari pengaruh beyond rational muncul dari aspek sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terbatas hanya pada kebutuhan untuk bersosialisasi saja.
Namun, juga untuk menggunakan orang-orang di sekelilingnya sebagai petunjuk bagaimana mereka harus berpikir, bersikap, termasuk bagaimana memilih produk. Influencer merupakan representasi dari sosok yang dipercaya dan diikuti oleh banyak orang sehingga secara tidak langsung membangun “social proof”.
Produk yang digunakannya bisa dipersepsikan sebagai produk yang digunakan banyak orang. Untuk itu, kita dengan lebih mudah lagi memilih untuk menggunakan produk yang digunakan atau direkomendasikan oleh mereka.
Selanjutnya, pemikiran bahwa influencer adalah representasi dari kelompok segmen yang lebih besar lagi pada akhirnya juga menciptakan FOMO (fear of missing out). Kalau sudah dipakai oleh influencer bakalan dipakai yang lain sih, jangan sampai ketinggalan, karena pasti akan dipakai banyak orang.
Dari sini, dorongan untuk membeli produk yang direkomendasikan influencer pun dimulai. Influencer marketing memang sudah diterima sebagai sebuah kewajaran di dunia marketing yang padahal ini adalah sebuah testamen dari bagaimana manusia itu tidak selalu logis.
Pada akhirnya kemampuan untuk mengerti pemikiran konsumen menjadi sebuah kewajiban jika kita ingin bisa bersaing. Fakta bahwa apa pun yang kita lakukan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari 3 program dasar otak manusia; seek pleasure, avoid pain, dan conserve energy.
Otak kita begitu malasnya untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan. Menuruti apa kata influencer adalah bukti bagaimana otak kita sering kali memilih shortcut, tanpa perlu repot-repot menganalisis pilihan-pilihan yang ada secara detail.
“Sudahlah kalau direkomendasikan oleh dia, kita sih tutup mata, pasti bagus.” Begitu pikir otak malas kita. Pertanyaan besarnya adalah seberapa jauh kita sebagai brand owner yang memanfaatkan influencer marketing mau mengerti bagaimana hal ini bekerja. Dus, brand owner bisa memilih influencer yang tepat ketimbang sekadar hitung-hitungan matematis logis.