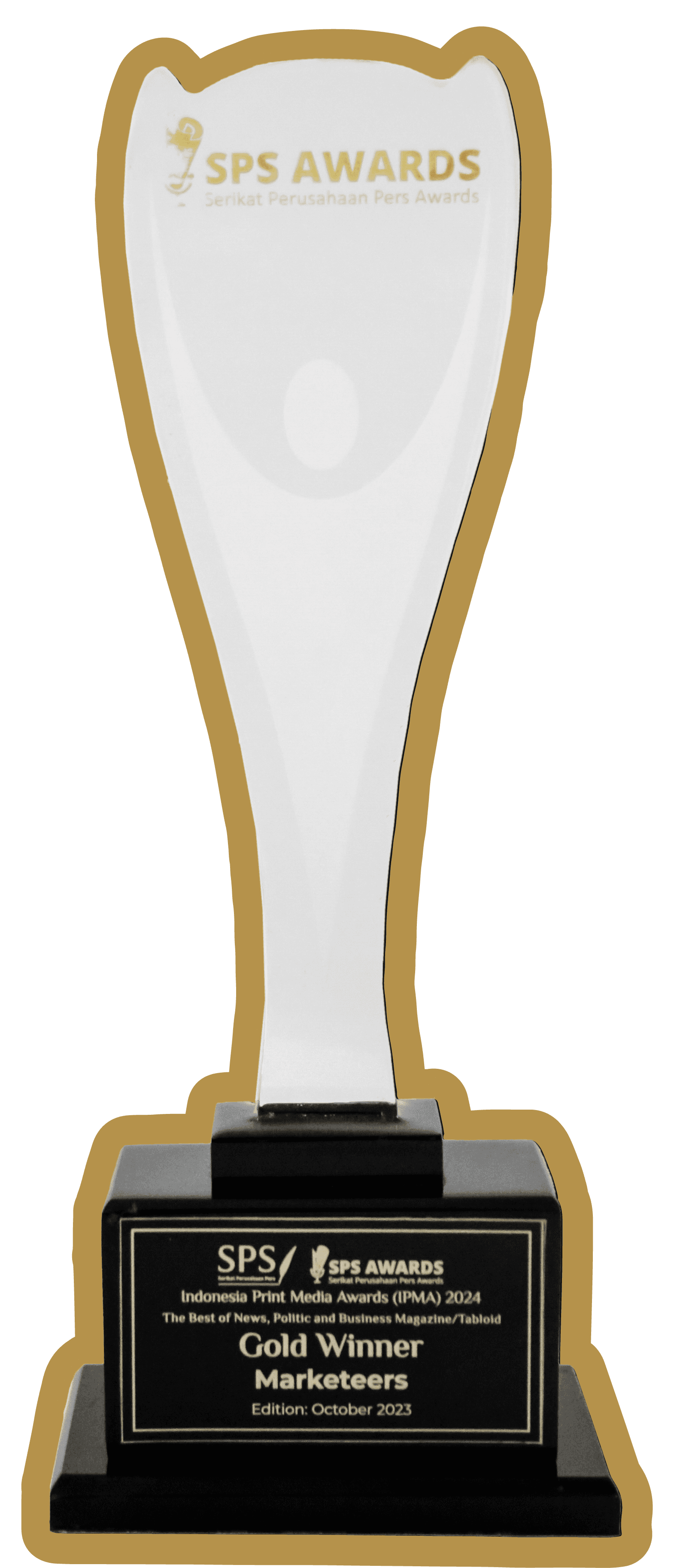Oleh Nadia Yustina,
Founder Amity Asia Agency
Lepas dari segala riuh rendah sensasi dan gemerlap imajinya, satu fakta yang tidak terhindarkan adalah industri musik kita sudah lama ‘sakit’. Penyebab utamanya adalah karena kita terlambat membangun peraturan serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk melindungi dan mengelola hak para musisi. Bisa dibilang perubahan ini baru dimulai pada 2014 dengan diterbitkannya Undang-undang Hak Cipta. Bandingkan dengan negara lain ketika pemain utama industri ini mulai fokus membenahi hal tersebut sejak awal dekade ’70-an.
Selama empat dekade ketertinggalan itu, apa yang berlaku di ekosistem industri musik Indonesia lebih banyak mengacu pada best practices dan learnings yang dialami oleh pelakunya terutama di pasar domestik. Alhasil, banyak hal mendasar yang belum memenuhi dengan apa yang umum berlaku di ekosistem industri musik global.
Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Hak Cipta, perkembangan teknologi digital yang makin pesat juga memiliki peran signifikan dalam mengubah keadaan. Setidaknya, kedua hal itu cukup punya pengaruh kuat dalam memberi empowerment bagi musisi-musisi generasi baru.
Contoh yang paling mendasar bisa dilihat di sisi produksi dan distribusi. Digitalisasi di segala lini, membuka kemungkinan yang lebih besar bagi siapa pun untuk menciptakan dan memasarkan lagunya dengan sangat mudah. Ini tentu saja berdampak positif dan memicu munculnya begitu banyak musisi baru luar biasa yang sebelumnya tak terdeteksi oleh audiens bahkan label sekalipun.
Dari sisi promosi, perkembangan teknologi juga menyebabkan musisi-musisi tersebut semakin leluasa menembus berbagai batas dalam menghampiri peminat karyanya. Pun melampaui hingga batas-batas negara. Karya dan berita tentang mereka lebih mudah terdengar di segala penjuru dunia. Masalah promosi yang identik dengan dana besar yang selalu menjadi kendala di masa lalu – jika tak berada di bawah sayap label besar – kini tak lagi meresahkan bagi musisi-musisi tersebut. Bagi mereka, kini sudah begitu banyak celah dan kesempatan yang bisa dieksplorasi di luar jalur-jalur promosi dan publikasi konvensional.
Persaingan yang ada saat ini pun bergeser, tak lagi berada di level teknis. Melainkan sudah memasuki ranah kreativitas dan jejaring yang dimiliki oleh masing-masing musisi. Kemampuan dan kejelian dalam mengelola kedua hal tersebut, utamanya secara digital, menjadi sebuah amunisi utama untuk bisa bertahan di tengah persaingan.
Ini langsung terbukti ketika masa pandemi menerjang pada kuartal awal tahun lalu. Saat industri lain yang mengandalkan keberadaan fisik terpukul sangat keras, industri musik masih bisa berkelit dan tidak ikut mandek. Pelaku industri musik yang langsung berteriak pada saat itu adalah mereka yang terlalu menggantungkan penghasilannya pada live performance. Tapi bagi musisi-musisi yang sudah mulai sejak awal mengelola aset digitalnya, pandemi tidak terlalu ber-impact besar. Weird Genius adalah salah satu contoh talenta yang justru semakin bersinar pada saat pandemi. Tingginya peningkatan jumlah karya musik orisinal yang di-upload di Digital Streaming Platform (DSP) seperti Spotify maupun platform video macam YouTube selama masa pandemi tahun 2020 lalu bisa menjadi indikator bahwa industri musik is still very much in business.
Dengan segala kemudahan yang dimungkinkan oleh perkembangan teknologi itu juga, saat ini banyak musisi yang memosisikan dirinya sebagai sebuah brand. Sebut saja Taylor Swift atau BTS. Walau tetap menjadikan musik sebagai inti dari bisnis mereka, saat ini mereka sudah tampil sebagai brand yang sukses menangguk berbagai revenue stream baru terutama di luar musik. Nama mereka sudah setara valuasinya dengan startup-startup bahkan yang berkategori unicorn. Dan, inilah yang menjadi impian musisi-musisi lain, termasuk sebagian musisi kita.
Namun, perjalanan kita masih sangat jauh untuk mengejar ketertinggalan dari apa yang sudah berlangsung di ekosistem musik internasional. Di sinilah dirasa perlunya ada percepatan yang harus diprakarsai secara fokus oleh pihak pemerintah dan pelaku industri musik sendiri.
Kegelisahan terhadap hal-hal itu yang melatari didirikannya Amity Asia Agency. Kami percaya betul bahwa Indonesia tidak akan kekurangan musisi kreatif. Namun tanpa pengelolaan yang fokus dan serius, kami juga khawatir musisi-musisi tersebut akan bernasib begitu saja. Tenggelam, tergerus oleh invasi musisi mancanegara yang kini ibaratnya sudah berada di ambang pintu.
Sedikit gambaran, wilayah Asia Tenggara seperti the last frontier dalam bisnis musik global. Saat wilayah lain di dunia dengan populasi besar sudah dikapling-kapling oleh para raksasa industri dan sudah di-capitalize secara masif, kini mereka mencari “kapling” lain. Dan Asia Tenggara adalah jawabannya.
Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, tentunya perhatian cukup besar tertuju pada Indonesia. Namun, kita harus jeli menanggapinya. Sebagian besar dari perhatian itu adalah lebih meng-capitalize market Indonesia. Contoh jelasnya, dari sekian banyak artis yang berhasil mendapat kontrak dengan perusahaan internasional, market share terbesar mereka tetap berada di Indonesia. Sebenarnya ini tak jadi masalah. Tapi alangkah akan lebih baik bila para musisi Indonesia ini juga bisa mendapatkan market share yang sama besarnya dengan negara lainnya.
Upaya ini bisa didukung oleh pelaku industri lain, salah satunya dengan membuat kerja sama strategis bersama musisi-musisi itu dalam mengampanyekan brand atau produknya dan tak hanya melibatkan mereka sebagai duta. Kerja sama strategis ini adalah kolaborasi menyeluruh yang setara dan mutualisme bagi kedua belah pihak.
Seperti yang pernah dilakukan oleh Kelompok Penerbang Roket (KPR) dengan sepatu Compass beberapa waktu lalu, misalnya. Peran band rock asal Jakarta ini tak hanya menjadi duta bagi Compass, melainkan juga dilibatkan untuk ikut mendesain dan menjaga kualitas signature model-nya sendiri. Personil dan manajemennya diajak urun pendapat memikirkan strategi marketing produk itu terutama kepada fans loyalnya. Berbekal pemahaman KPR terhadap sebaran loyalisnya, mereka mengusulkan untuk menggelar konser di beberapa kota yang paling besar jumlah loyalisnya, sekaligus launching dan penjualan langsung produk KPR x Compass. Hasilnya, di tiap kota yang disinggahi, produk itu sold out dalam waktu rata-rata tak lebih dari 30 menit.
Ini membuktikan bahwa daya tarik musik dan musisinya masih menjadi elemen berharga. Dan, kolaborasi antara sebuah brand yang bagus dengan band yang sangat peduli dalam mengelola para loyalisnya, bisa menghasilkan sesuatu yang fenomenal dan memuaskan bagi kedua belah pihak.
Adanya kolaborasi dengan prinsip kesetaraan semacam ini juga yang akan membentuk landasan pemahaman yang kuat bagi pelaku industri musik, khususnya hal-hal yang berlaku di ekosistem industri secara lebih luas. Ini tentunya akan menjadi modal berharga bagi mereka ketika bersaing di market global. Tak hanya sebagai musisi tapi juga sebagai sebuah brand yang solid.
Bermodal keyakinan itu dan expertise yang didapat dari experience tiap awaknya, saat ini Amity Asia Agency berusaha dengan segenap daya untuk berkembang, melakukan networking serta berusaha mengisi gap-gap kecil yang dibutuhkan oleh musisi-musisi tersebut. Tujuannya agar mereka bisa produktif dan meniti karier untuk meraih mimpi-mimpinya. Apakah Anda salah satu musisi itu?
Nadia Yustina adalah Founder Amity Asia Agency,
sebuah booking agency di Jakarta yang mewakili
sekurangnya 50 artis dari berbagai genre musik
dan kini tergabung dalam ekosistem GDP Venture.